-Refleksi kuliah Observasi dan Wawancara Humanistik.
Ini adalah secuplik materi kuliah dengan dosen yang cukup “Humanistik”. Saya coba pahami melalui analogi berikut. Kita mau muntah, sedang di tempat umum. Jadi harus ke kamar mandi dulu karena muntah di tempat umum adalah hal memalukan. Begitu juga dengan mengekspresikan emosi, perlu pergi ke tempat yang kondusif dulu supaya tidak dianggap aneh-aneh oleh orang lain. Dosen saya mengatakan, kita orang Indonesia dibiasakan untuk meniadakan emosi, “Ga boleh nangis, marah, dsb”. Apak akibatnya ? Kita menjadi tidak peka dengan emosi diri sendiri, sehingga tidak bisa mendeteksinya. Yang terjadi hanyalah ada gejolak dalam diri tanpa tahu apa itu. Contohnya, ada pengalaman pahit pernah disakiti oleh bapaknya. Rasanya benci, marah, ada dendam, tapi bingung harus bagaimana karena yang menyakiti adalah orang tuanya. Dia hanya memendam perasaan itu, disimpan, ditutupi, dan berusaha dilupakan karena takut. Bapak & ibunya mungkin sering mengatakan, “Marah sama orang tua itu durhaka, itu dosa”. Khawatir juga dilabel sebagai "Anak tidak berbakti pada orang tua" oleh orang-orang lain yang tahu. Dalam pikirannya, “Aku ga boleh menampakkan marah walaupun sebenernya benci sama bapak, ya sudahlah, lupakan saja.” Namun, sebenarnya di dalam hatinya yang terdalam, dia belum memaafkan. Hanya saja itu diingkari, seakan-akan tidak merasakan apapun. Suatu saat emosi itu bisa terekspresikan, seperti meledak. Yang terjadi adalah bingung, “Kok aku seperti ini ya.. Inikah diriku ?” Ini gambaran contoh seseorang yang tidak mengenal emosi dirinya. Kenal saja tidak, apalagi meregulasinya.
Aplikasinya dalam konseling.. Aliran humanistik menekankan empati dan emosi. Klien dibiarkan untuk memuntahkan emosinya karena belum tentu orang tahu apa yang tersembunyi di dalam dirinya (masih dalam level mental, belum sampai jiwa). Mungkin benci, sedih, marah, kecewa, dsb. Terkadang orang juga merasa berat menceritakan pengalamannya, saking beratnya masalah yang dihadapi sehingga bingung mulai cerita dari mana. Ada juga orang yang bersikeras dirinya baik-baik saja, pura-pura kuat, padahal dirinya rapuh. Mau menangis, teriak keras, mengumpat, semua dibiarkan sampai klien siap untuk bercerita dengan pikiran yang lebih jernih. Harapannya, klien sadar akan emosi dirinya, apa yang sedang terjadi dengan dirinya, tentu dengan bantuan psikolog. Seperti mengakui, “Oh, ternyata selama ini saya masih dendam dengan seseorang.”
Saya refleksikan lagi karena sempat berpikir, apakah pemikiran dan praktik seperti itu bisa diterima dalam perspektif Islam ? Saya kaitkan dengan materi tasawuf sejauh yang dipahami. Allah menampakkan penyakit hati tiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Bagi orang yang bertaubat, ditampakkannya penyakit hati merupakan hal penting karena individu bisa menyadarinya dan berniat melakukan perbaikan diri agar penyakit tersebut hilang sedikit demi sedikit. Dalam konteks konseling dan psikoterapi, konsep humanistik mungkin bisa diterapkan bagi orang yang terlanjur larut dalam syahwat aau hawa nafsunya tapi ada potensi untuk bertaubat. Emosi klien sengaja dimuntahkan, biarkan dia mengekspresikan sesuka hati. Setelah emosi mereda dan klien bisa diajak berpikir, psikolog membantunya melakukan refleksi atas ekspresi emosi yang barusan ditampilkan. Caranya bisa dengan melabel emosi tersebut dan mengidentifikasi jenis penyakit hati apa yang sedang dideritanya. Harapannya adalah klien akhirnya mengenal emosi yang sedang dialami sekaligus penyakit hati yang mengendap sekian lama. Pilihan tetap ada pada klien: apakah ingin sembuh dari penyakit itu atau tetap menyimpannya. Jika ingin sembuh, proses konseling bisa menjadi titik awal untuk taubat.
Orang yang sehat jiwanya adalah yang dapat mengenali dan meregulasi emosinya, bukan mengingkari adanya emosi itu. Ketika sedang marah di tempat umum, dia sadar bahwa dirinya sedang marah. Kesadaran bahwa marah itu menguras energi dan berdampak buruk bagi dirinya, mendorongnya berusaha untuk meregulasinya, yaitu dengan tidak mengekspresikannya. Salah satu caranya bisa dengan istighfar. Terkesan simpel ya, ketika diuraikan secara rasional.. Namun, pada kenyataannya akan sangat sangat sulit untuk dipraktikkan, terutama bagi orang yang tidak menyadari emosinya.
Jika memang emosi baik positif atau negatif harus diingkari, untuk apa Allah menciptakan emosi senang, geli, kecewa, sedih, takut, marah, dan sebagainya ? Apa jadinya hidup tanpa emosi ? Emosi itu diregulasi, bukan diingkari.
Selamat mencoba ! :)

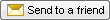


0 komentar:
Posting Komentar